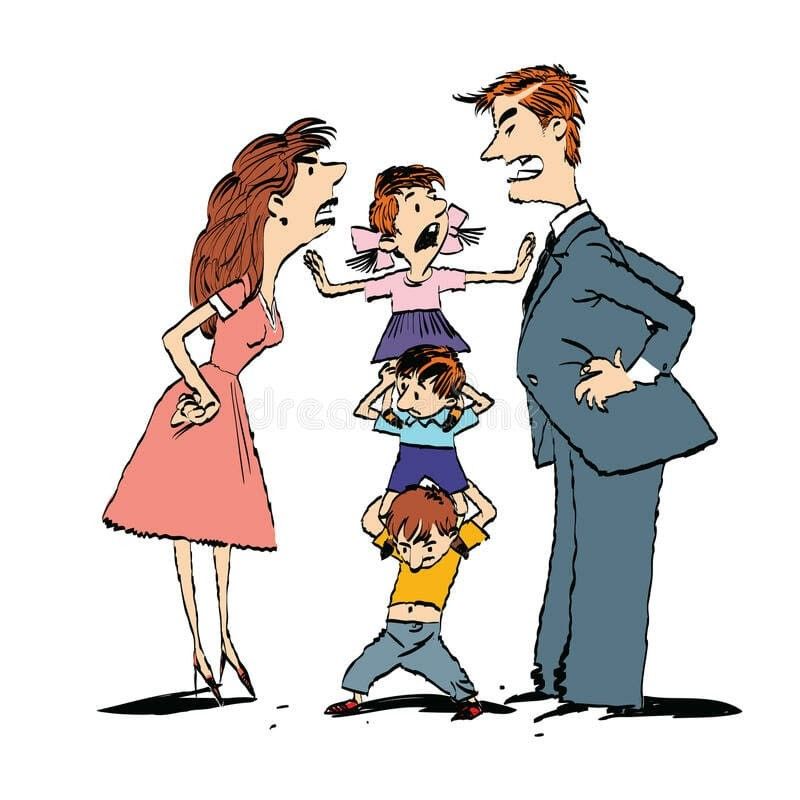
Cerai antara Fikih dan Hukum Negara: Menyatukan Norma Ilahi dan Realitas Sosial
Oleh: Agus Gunawan
Abstrak
Perceraian (ṭalāq) merupakan peristiwa hukum yang menyentuh dimensi spiritual, sosial, dan legal sekaligus. Dalam fikih Islam, cerai dipahami sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri pernikahan yang tidak lagi membawa kemaslahatan. Sementara dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur melalui sistem peradilan yang menekankan tertib hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Artikel ini membahas perbandingan konseptual dan prosedural antara hukum fikih dan hukum negara mengenai perceraian, serta menawarkan refleksi integratif agar keduanya tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi.
Pendahuluan
Pernikahan dalam Islam merupakan mīṡāqan ghalīẓan—ikatan yang kokoh dan suci antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisā’ [4]: 21. Namun, Islam juga mengakui kenyataan bahwa tidak semua pernikahan dapat dipertahankan. Karena itu, perceraian menjadi solusi terakhir yang bersifat darurat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ
“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”
(HR. Abū Dāwūd, no. 2177)
Dari sini, tampak bahwa perceraian dibolehkan, namun dengan kehati-hatian moral dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, perceraian juga diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum negara menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus melalui keputusan pengadilan, bukan semata tindakan pribadi.
Konsep Perceraian dalam Fikih Islam
- Dasar Hukum
Fikih Islam menjadikan al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber utama dalam membahas perceraian. QS. al-Baqarah [2]: 229 menyebutkan:
“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”
Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi upaya rekonsiliasi sebelum perceraian final. Fikih klasik membagi talak menjadi beberapa kategori:
- Talak raj‘i (talak yang dapat dirujuk selama masa iddah),
- Talak bain sughra (tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru),
- Talak bain kubra (tidak bisa kembali kecuali setelah istri menikah dengan suami lain dan berpisah secara sah).
- Subyek dan Prosedur
Dalam fikih, talak berada di tangan suami. Suami memiliki hak menjatuhkan talak dengan lafal tertentu (ṣarīḥ atau kināyah), baik diucapkan secara lisan maupun tertulis. Namun, fikih juga mengenal bentuk cerai yang berasal dari pihak istri, seperti:
- Khulu‘: cerai dengan tebusan dari pihak istri,
- Fasakh: pembatalan nikah oleh hakim karena sebab tertentu (cacat, kekerasan, atau tidak memberi nafkah),
- Li‘ān dan Ila’: cerai akibat sumpah tuduhan zina atau tidak berhubungan intim dalam waktu lama.
Fikih memandang perceraian sah secara agama apabila memenuhi syarat dan rukun, tanpa mensyaratkan adanya campur tangan pengadilan. Meski demikian, prinsip moral menekankan agar perceraian dilakukan dengan iḥsān (cara baik), tanpa permusuhan atau pengabaian hak.
Konsep Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia
- Dasar Hukum
Dalam konteks hukum negara, perceraian diatur dalam:
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38–41;
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI–XVII.
Prinsip utamanya adalah bahwa setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya damai. Tanpa putusan pengadilan, perceraian tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara.
- Prosedur Perceraian
Perceraian dapat diajukan oleh:
- Suami melalui permohonan talak ke Pengadilan Agama,
- Istri melalui gugatan cerai (khulu‘ atau fasakh).
Tahapan umumnya meliputi:
- Pengajuan permohonan atau gugatan ke pengadilan;
- Upaya mediasi atau perdamaian;
- Pembacaan/pemeriksaan Gugatan/permohonan;
- Jawab-menjawab (Jawaban, replik, duplik);
- Pemeriksaan bukti dan saksi;
- Putusan hakim yang menetapkan sah atau tidaknya perceraian;
- Pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA).
Prosedur ini menegaskan peran negara sebagai penjaga tertib sosial dan pelindung hak-hak perempuan serta anak.
Perbandingan Fikih dan Hukum Negara
| Aspek | Fikih Islam | Hukum Positif Indonesia |
| Sumber hukum | Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas | UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, KHI |
| Pihak yang berwenang menceraikan | Suami (talak), istri (khulu‘, fasakh) | Pengadilan Agama melalui putusan |
| Syarat sah perceraian | Ucapan atau niat talak yang sah | Putusan pengadilan dan pencatatan resmi |
| Tujuan utama | Menjaga kehormatan dan keadilan syar‘i | Menjamin kepastian hukum dan perlindungan sosial |
| Dampak hukum | Berlaku sejak talak dijatuhkan | Berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap |
Perbedaan mendasar terletak pada tata cara dan otoritas yang mengesahkan perceraian. Fikih menekankan aspek niat dan lafaz, sedangkan hukum positif menekankan aspek administratif dan perlindungan hukum. Namun, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yakni mencegah kemudaratan dan menjaga kemaslahatan keluarga.
Dialektika dan Harmonisasi antara Fikih dan Hukum Negara
Dalam praktik sosial, tidak jarang terjadi ketegangan antara hukum agama dan hukum negara, misalnya ketika seorang suami menjatuhkan talak di luar pengadilan. Secara fikih, talak itu sah, tetapi secara hukum negara tidak memiliki kekuatan yuridis. Akibatnya, muncul persoalan administrasi seperti status istri, hak nafkah, maupun hak asuh anak.
Untuk menjembatani hal ini, KHI berfungsi sebagai jembatan harmonisasi antara fikih dan hukum positif. KHI mengadopsi prinsip-prinsip fikih klasik namun menyesuaikannya dengan kebutuhan modern, seperti perlunya mediasi, pencatatan resmi, dan pengawasan hakim. Pendekatan ini merupakan bentuk fiqh dustūrī (fikih ketatanegaraan), yang mengakui peran negara sebagai wali amr dalam menjaga kemaslahatan umat (ḥifẓ al-niẓām).
Harmonisasi tersebut sesuai dengan kaidah fikih:
تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
“Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”
(al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir, h. 121)
Maka, kewajiban mencatat perceraian di pengadilan bukanlah penyimpangan dari syariat, melainkan bagian dari pelaksanaan maqāṣid al-syarī‘ah dalam konteks modern: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).
Refleksi dan Tantangan Sosial
Fenomena perceraian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, terutama perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Faktor penyebabnya beragam: ekonomi, kekerasan rumah tangga, ketidakharmonisan, hingga pengaruh media sosial. Dalam konteks ini, fikih dan hukum negara memiliki peran penting untuk mengedukasi masyarakat agar memandang pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang bernilai transendental.
Diperlukan sinergi antara lembaga keagamaan (seperti KUA, pesantren, dan majelis taklim) dengan lembaga hukum (pengadilan agama, lembaga konsultasi hukum) agar perceraian dapat diminimalkan melalui pendidikan pra-nikah, mediasi, dan pendampingan psikologis.
Penutup
Perceraian antara fikih dan hukum negara bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu tujuan: menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga. Fikih memberikan fondasi nilai-nilai spiritual dan etika dalam berumah tangga, sedangkan hukum negara memastikan adanya tertib sosial dan perlindungan hak setiap warga. Dengan pendekatan integratif—antara norma ilahi dan realitas sosial—perceraian dapat dikelola secara bijak, manusiawi, dan bermartabat.
Daftar Pustaka
- Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Al-Qur’an al-Karīm.